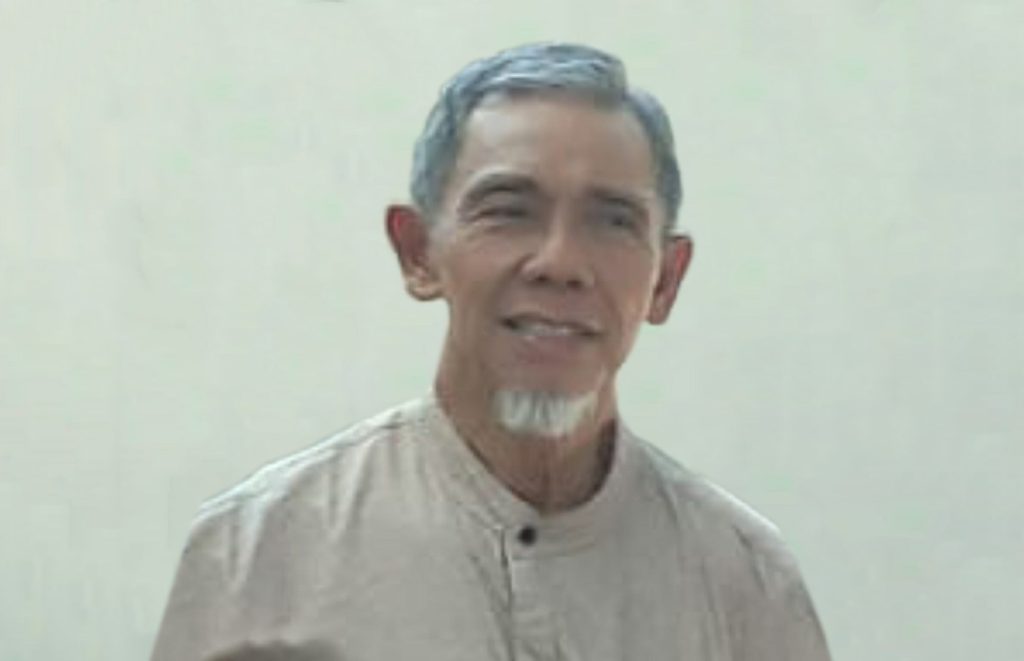Oleh Kemas Adil Mastjik (Wakil Ketua Bidang Pendidikan Dewan Da’wah Jatim)
Dewandakwahjatim.com, Surabaya – Seorang ibu bercerita: ”Anak saya selalu menutup pintu kamar. Saya pikir dia sedang belajar. Tapi suatu malam saya masuk diam-diam. Ternyata dia menangis, memeluk gawai, dan berbisik ‘Aku lelah, tapi tak ada yang peduli”.
Betapa banyak anak seperti itu, menyimpan luka dalam diam karena tidak tahu bagaimana berbicara dengan orang tuanya. Atau mungkin orang tuanya tidak menyediakan telinga yang mendengar, dan hati yang mengerti (Fathur Rohman, “Wahai Ibu Bapakku, Selamatkanlah Aku”, h. 5,6).
Potret Itu
Mendidik dengan omongan ialah mengajar mereka supaya bersifat benar, jujur, berani, sabar, amanat dan lain lain sifat, perangai dan kelakuan baik; demikian juga mengajar mereka supaya menjauhi sifat sifat dusta, khianat, penakut, amarah, dan lain lain sifat / perangai jahat. Cara mengajar dengan teori ini amat sedikit bekasnya. Terutama pada anak anak yang masih kecil. Didikan yang sangat bisa diharap buahnya, ialah dengan perbuatan (A.Hassan, “Hai anak cucuku!”, h. 307).
Ungkapan “anak saleh adalah anugerah” kerap kita dengar di tengah masyarakat. Pernyataan itu benar, namun sering dipahami secara keliru seolah kesalehan anak hadir tanpa proses. Padahal, dalam perspektif Islam, psikologi, dan ilmu pendidikan, anak saleh bukanlah kebetulan. Ia lahir dari rangkaian ikhtiar panjang, pengasuhan sadar, keteladanan, serta doa yang terus-menerus dipanjatkan.
Islam sejak awal menegaskan bahwa keluarga adalah fondasi utama pembentukan kepribadian. Rasulullah ﷺ bersabda, “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi” (HR Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan betapa besar pengaruh lingkungan keluarga dalam membentuk arah hidup dan karakter anak.
Belajar dari Relasi
Psikologi perkembangan menegaskan bahwa tahun-tahun awal kehidupan anak—khususnya usia 0–7 tahun—merupakan masa krusial pembentukan kelekatan (attachment). Teori attachment yang dikembangkan John Bowlby menunjukkan bahwa hubungan emosional yang hangat, aman, dan responsif antara orang tua dan anak berpengaruh besar terhadap empati, kontrol diri, dan moralitas anak di masa depan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengimbau orang tua di Indonesia membangun kembali kedekatan emosional dengan anak. Imbauan ini dinilai sangat mendesak, terutama dalam konteks pendampingan penggunaan gawai dan internet, sebagai langkah preventif untuk mencegah kekerasan terhadap anak (https://ameera.republika.co.id).
Anak yang tumbuh dalam keluarga penuh kasih, konsistensi, dan rasa aman cenderung memiliki regulasi emosi yang baik. Dalam konteks kesalehan, ini menjadi fondasi penting: anak lebih mudah menerima nilai, nasihat, dan teladan agama ketika hatinya merasa aman dan dihargai. Sebaliknya, pola asuh keras, abai, atau penuh konflik sering melahirkan anak yang patuh secara semu, namun rapuh secara batin.
Psikologi modern juga menegaskan bahwa anak meniru lebih banyak daripada mendengar. Konsep modeling dalam teori belajar sosial Albert Bandura menjelaskan bahwa perilaku orang tua—bukan sekadar kata-kata—menjadi “kurikulum hidup” bagi anak. Orang tua yang jujur, disiplin, menjaga lisan, dan beribadah dengan konsisten sedang mengajarkan kesalehan tanpa ceramah panjang.
Rumah sebagai Sekolah Nilai
Dalam ilmu pendidikan, keluarga dikenal sebagai pendidikan informal yang justru paling menentukan. Sekolah dapat mengajarkan pengetahuan, tetapi rumah membentuk sikap dan kebiasaan. Penelitian-penelitian pendidikan menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak—mendampingi belajar, berdialog, dan memberi contoh—berkorelasi positif dengan karakter, motivasi, dan perilaku prososial anak.
Kesalehan anak bukan hanya soal kemampuan membaca doa atau menjalankan ritual, tetapi juga akhlak: jujur, amanah, peduli, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai ini tumbuh melalui pembiasaan. Pendidikan karakter menekankan pentingnya habituation—pengulangan perilaku baik secara konsisten—yang paling efektif dilakukan di rumah.
Di sinilah peran ayah dan ibu menjadi sangat strategis. Ayah bukan sekadar pencari nafkah, dan ibu bukan hanya pengasuh fisik. Keduanya adalah pendidik nilai. Sinergi ayah-ibu dalam menerapkan aturan, memberi kasih sayang, dan menegakkan disiplin yang adil akan menciptakan ekosistem rumah yang kondusif bagi tumbuhnya kesalehan.
Ikhtiar dan Doa yang Menyatu
Islam tidak memisahkan ikhtiar dan doa. Al-Qur’an mengabadikan doa para nabi terkait anak dan keturunan, seperti doa Nabi Ibrahim, “Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat” (QS Ibrahim: 40). Ini menunjukkan bahwa kesalehan anak adalah harapan spiritual yang diperjuangkan, bukan ditunggu.
Doa tanpa pengasuhan adalah harapan kosong, sementara pengasuhan tanpa doa berpotensi melahirkan kelelahan batin. Keduanya harus berjalan beriringan. Orang tua mendidik dengan ilmu dan kesabaran, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan tawakal.
Investasi Peradaban dari Rumah
Anak saleh tidak lahir dari kebetulan, tetapi dari rumah yang hidup dengan nilai. Dari orang tua yang mau belajar, bercermin, dan memperbaiki diri. Dari suasana rumah yang menghadirkan cinta, adab, dan keteladanan. Dalam konteks yang lebih luas, pengasuhan keluarga adalah investasi peradaban. Anak-anak hari ini adalah wajah umat di masa depan.
Maka, sebelum bertanya “mengapa anak sulit dinasihati?”, barangkali kita perlu bertanya lebih jujur: nilai apa yang setiap hari ia lihat di rumah? Dari sanalah kesalehan tumbuh—perlahan, tetapi pasti—atas izin Allah. Wallahua’lam. (Rewwin, 15 Januari 2026)
Admin: Kominfo DDII Jatim
Editor: Sudono Syueb